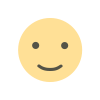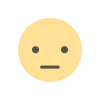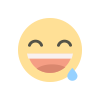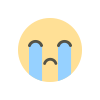Haruskah Terbitkan KTP, Bayar Petugas?
Menjadi rahasia umum jika penerbitan dokumen kependudukan terkenal ribet jika warga mengurusnya dengan cara gratisan

SUARAJATIMPOST.COM - Bukan menjadi rahasia lagi bagi masyarakat Indonesia, dalam hal mengurus atau menerbitkan sebuah dokumen kependudukan diharuskan membayar sejumlah uang.
Padahal, penerbitan dokumen kependudukan sepenuhnya gratis bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 79A Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Dokumen kependudukan yang gratis diurus di Dukcapil di antaranya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) , Akta kelahiran dan Akta kematian.
Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) adalah tempat yang konon terkenal ribet. Di kantor tersebut juga terkenal dengan antrean yang panjang, petugas pelayanan yang cuek hingga, blanko yang selalu dibilang habis.
Namun, kantor tersebut menjadi tak ribet dengan pelayanan yang super ramah bagi warga yang hendak menerbitkan dokumen kependudukan dengan membayar sejumlah uang.
Dilansir dari aclc.kpk.go.id, terdapat sebuah cerita menarik tentang penerbitan dokumen kependudukan yang terkenal ribet jika tanpa uang pelicin.
Kirana melangkah ragu ke loket, dengan map hijau yang sudah diisi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. "Selamat pagi, Mbak," sapanya pada petugas perempuan yang terlihat sibuk menatap layar komputer.
Petugas itu menoleh sekilas. "Ada keperluan apa, Mbak?"
"Mau mengurus KTP baru," jawab Kirana sambil menyerahkan mapnya.
Petugas itu membuka map, mengecek isi dengan cepat, lalu menatap Kirana sambil tersenyum kaku. "Blanko KTP-nya sedang habis, Mbak. Untuk sementara, kami hanya bisa menerbitkan surat keterangan (suket) pengganti."
Kirana terdiam sejenak, kecewa. "Jadi, kapan KTP saya bisa jadi?"
"Kami akan menghubungi Mbak kalau blanko sudah tersedia. Bisa lewat telepon atau email," ujar petugas itu.
Kirana pulang dengan hati berat. Padahal, besok dia harus ke Jakarta, ada urusan kerja. Ia bingung jika harus membawa suket ke mana-mana, apalagi naik kereta sekarang harus pindai identitas. Namun, ia tak punya KTP. Lalu bagaimana? Ia berpikir keras.
Ia bercerita kepada ibunya dan hanya bisa menghela napas panjang. "Kamu yang sabar, ya. Begitulah di sini. Kalau nggak mau ribet, biasanya orang bayar."
Kirana tertegun mendengar ucapan ibunya. Bayar? Bukankah mengurus KTP itu hak warga negara? Tapi ia tidak ingin berprasangka buruk. Mungkin memang benar blanko sedang habis.
Beberapa hari kemudian, Kirana mendengar cerita lewat ibunya bahwa tetangganya, Bu Siti, baru saja menerima KTP baru. "Ibu Ana, Kirana sudah dapat KTP baru?"
"Belum, Bu. Katanya blanko habis," jawab Ibu Ana.
Bu Siti tertawa kecil. "Saya baru saja dapat KTP. Cepat sekali prosesnya."
"Lho, kok bisa, Bu?"
"Ya, saya kasih uang 500 ribu ke petugas. Tiga hari langsung jadi."
Ibu Kirana hanya terdiam mendengar cerita itu. Hatinya penuh tanda tanya. Jika Bu Siti bisa, kenapa anaknya tidak? Pada bulan berikutnya, Kirana kembali ke Dinas Kependudukan, kali ini dengan tekad untuk meminta penjelasan.
"Maaf, Mbak," ulang petugas yang sama, "Blanko KTP masih habis. Mbak menunggu kabar saja dari kami."
"Tapi, Bu Siti, tetangga saya, baru dapat KTP bulan lalu. Katanya, diurus di sini juga," ujar Kirana, berusaha menahan nada jengkelnya.
Petugas itu terdiam sejenak, lalu menggeleng tegas. "Kalau seperti itu, mungkin lewat jalur belakang, saya tidak tahu.”
Kami di sini zona integritas, antikorupsi. Tidak mungkin menerima uang seperti itu,” ia menjelaskan.
"Tapi kenapa harus ada jalur belakang? Bukankah ini hak saya sebagai warga negara?" tanya Kirana, suaranya bergetar oleh emosi.
Petugas itu hanya menunduk, melanjutkan pekerjaannya tanpa menjawab. Kirana pulang dengan hati campur aduk—antara marah, sedih, dan pasrah. Di rumah, ia membuka ponselnya dan menulis unggahan di media sosial.
"Mengurus KTP di Dinas Kependudukan. Katanya blanko habis. Tapi tetangga saya bisa cepat dapat KTP baru setelah membayar 500 ribu. Kenapa sistem yang seharusnya mudah jadi dipersulit? Bukankah ini hak kita?"
Unggahan itu mendapat banyak respons. Dalam hitungan hari, kisah Kirana menjadi viral. Banyak warganet membagikan pengalaman serupa. Media mulai meliput, dan Kirana diundang ke sebuah acara televisi.
"Saya hanya ingin keadilan," ujar Kirana dalam wawancara itu. "Saya hanya ingin hak saya dipenuhi tanpa harus membayar lebih."
Kepala Dinas Kependudukan Kota akhirnya memberi respons setelah cerita Kirana viral di medsos. Ia meminta maaf dan berjanji akan menyelidiki kasus tersebut. Hasilnya, beberapa oknum terbukti menerima uang untuk mempercepat proses pembuatan KTP.
"Kami mohon maaf atas kelalaian ini. Kami pastikan ini ulah oknum, bukan kesalahan sistem," ujar Kepala Dinas dalam konferensi pers.
Bahkan Bupati setempat ikut memberikan pernyataan. "Kami akan meningkatkan pengawasan. Ini bukan bagian dari sistem kami, ini murni perbuatan oknum," katanya dengan nada normatif.
Namun, cerita itu tidak berakhir di situ. Beberapa bulan kemudian, Kirana menerima telepon dari seorang wartawan.
"Mbak Kirana, kami baru saja menemukan fakta bahwa praktek pungutan liar itu sudah terjadi bertahun-tahun, melibatkan banyak pihak. Ada tanggapan?"
Kirana terdiam sejenak. Ia menghela napas panjang, mencoba menahan emosi. "Saya sudah tidak kaget. Dari awal saya tahu ini bukan soal oknum. Ini sistem yang salah. Tapi setidaknya, sekarang semua orang tahu."
Wartawan itu terdiam, lalu mengucapkan terima kasih. Setelah menutup telepon, Kirana menatap KTP barunya yang akhirnya selesai tanpa pungutan tambahan. Tapi di balik itu, ia merasa getir. Haknya sebagai warga negara ternyata bukan sesuatu yang bisa ia dapatkan begitu saja—harus ada perjuangan, harus ada suara yang lantang. (**)
Sumber : aclc.kpk.go.id
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?